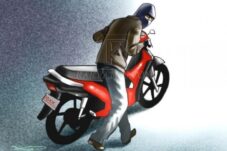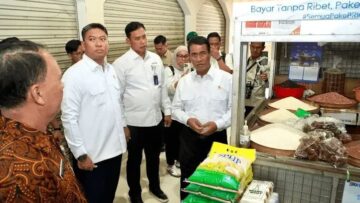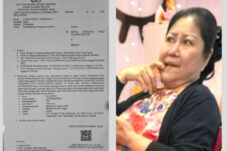Oleh: Arifai Ilyas
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Tarakan Koordinator Kalimantan Utara
DI tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 60 persen dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya termanfaatkan karena berbagai kendala klasik, mulai dari akses permodalan, keterbatasan pasar, hingga rendahnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu peluang besar yang belum optimal digarap adalah pasar pemerintah sebuah ceruk ekonomi strategis yang memiliki kapasitas anggaran besar dan stabil melalui mekanisme belanja negara.
Pasar Pemerintah: Ruang Ekonomi yang Stabil dan Terukur
Setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan belanja barang dan jasa yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Dalam APBN 2025, misalnya, belanja pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa diperkirakan melampaui Rp1.200 triliun. Angka ini merepresentasikan pasar yang sangat besar, stabil, dan relatif bebas dari fluktuasi ekonomi global.
Namun, ironi yang terjadi selama ini adalah sebagian besar dari belanja pemerintah tersebut justru dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara partisipasi UMKM masih rendah. Padahal, jika sebagian porsi belanja publik itu diarahkan kepada UMKM, dampaknya akan sangat luas mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan daya beli masyarakat, hingga penguatan rantai pasok dalam negeri.
Menyadari potensi ini, pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan porsi minimal 40 persen belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, terutama yang dihasilkan oleh UMKM.
Selain itu, platform digital seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan e-Katalog Lokal juga dirancang untuk memperluas akses UMKM terhadap pasar pemerintah.
Menghubungkan UMKM dengan Pasar Pemerintah
Masalah utama bukan hanya pada ketersediaan regulasi, melainkan pada bagaimana UMKM dapat terhubung dan berdaya saing dalam sistem pengadaan pemerintah yang terstandar dan berbasis digital. Banyak pelaku UMKM belum memahami mekanisme tender, prosedur administrasi, atau persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah. Sebagian bahkan belum
terdaftar dalam sistem e-katalog karena belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikat produk yang dipersyaratkan.
Oleh karena itu, strategi inklusif harus dimulai dari penyederhanaan prosedur dan penguatan kapasitas. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator dengan menyediakan pendampingan teknis, pelatihan digitalisasi, dan sertifikasi produk bagi pelaku UMKM lokal.
Di sisi lain, lembaga pengadaan barang/jasa (LPSE) perlu memperkuat sistem e-katalog lokal yang mudah diakses, responsif, dan adaptif terhadap skala usaha kecil.
Beberapa daerah telah memulai praktik baik ini di Provinsi Jawa Tengah dengan meluncurkan katalog lokal dengan ratusan produk UMKM yang dapat langsung dibeli oleh satuan kerja pemerintah tanpa melalui tender. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat realisasi belanja daerah, tetapi juga menumbuhkan optimisme baru bagi UMKM untuk naik kelas melalui pasar pemerintah.
Katalis Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
Keterlibatan UMKM dalam pasar pemerintah tidak sekadar soal perluasan akses pasar, melainkan juga menjadi katalis peningkatan kualitas dan daya saing produk. Proses pengadaan yang terstandar mendorong pelaku UMKM untuk memperbaiki manajemen usaha, memperkuat pencatatan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan
legalitas.
Dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengadaan, UMKM sebenarnya sedang melakukan transformasi kelembagaan menuju tata kelola usaha yang lebih profesional. Ini merupakan langkah penting menuju peningkatan produktivitas dan kesiapan bersaing di pasar komersial, baik nasional maupun global.
Selain itu, keterlibatan dalam pasar pemerintah dapat memperkuat jaminan permintaan (demand assurance) bagi UMKM. Ketika pemerintah menjadi pembeli yang pasti dan berkelanjutan, pelaku usaha kecil memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan investasi, memperluas kapasitas produksi, dan merekrut tenaga kerja tambahan. Ini akan menciptakan
efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian lokal.
Digitalisasi Pengadaan dan Ekonomi Inklusif
Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi momentum penting untuk mempercepat inklusi ekonomi. Platform seperti e-Katalog Nasional dan e-Katalog Lokal bukan hanya alat administratif, melainkan juga ekosistem digital yang menghubungkan ribuan penyedia barang/jasa dengan pengguna anggaran pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Melalui sistem ini, UMKM dapat menampilkan produknya secara daring, menetapkan harga yang kompetitif, dan melakukan transaksi tanpa harus terjebak dalam birokrasi panjang.
Inovasi seperti marketplace pemerintah (Government Marketplace) bahkan membuka peluang baru bagi integrasi data lintas kementerian dan lembaga, yang memungkinkan pemantauan real-time atas seberapa besar belanja pemerintah terserap untuk produk UMKM.
Namun, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Masih banyak UMKM di daerah yang terkendala akses internet, perangkat, atau kemampuan mengoperasikan sistem digital. Maka, kebijakan afirmatif seperti pelatihan e-procurement, inkubasi digitalisasi UMKM, dan integrasi dengan ekosistem fintech menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan digital antara pelaku usaha besar dan kecil.
Peran Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Multisektor
Keberhasilan memaksimalkan pasar pemerintah untuk UMKM sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Sebagai pelaksana belanja publik terbesar di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi inklusif melalui tiga strategi utama.
Pertama, alokasi belanja afirmatif yakni memastikan minimal 40 persen anggaran pengadaan diarahkan ke produk dan jasa UMKM lokal. Ini bukan sekadar kepatuhan regulatif, tetapi bentuk keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat.
Kedua, pembentukan katalog lokal berbasis potensi daerah. Setiap daerah memiliki kekhasan produk, baik hasil pertanian, kerajinan, maupun industri kecil. Dengan mengembangkan katalog lokal yang terintegrasi, pemerintah dapat mendorong UMKM daerah untuk menembus pasar lintas wilayah tanpa kehilangan identitas lokalnya.
Ketiga, penguatan kolaborasi multisektor. Dunia usaha besar, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam ekosistem ini. Misalnya, perbankan dapat menyediakan skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bagi UMKM yang menjadi mitra pemerintah. Perguruan tinggi dapat berperan dalam pelatihan manajemen usaha dan sertifikasi produk, sedangkan sektor swasta dapat berkolaborasi dalam
bentuk kemitraan atau subkontrak.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Kunci keberlanjutan pasar pemerintah untuk UMKM terletak pada transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengadaan yang terbuka dan berbasis digital dapat meminimalisir praktik monopoli, percaloan, atau kartel pengadaan yang selama ini sering menjadi hambatan bagi pelaku kecil untuk ikut bersaing secara sehat.
Dengan penerapan prinsip value for money, pemerintah tidak hanya berfokus pada harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas, keberlanjutan, dan dampak sosial ekonomi. Inilah esensi dari pengadaan yang inklusif dan berorientasi pembangunan: memastikan setiap rupiah belanja publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dari Belanja ke Pembangunan: Paradigma Baru Ekonomi Nasional
Mengoptimalkan pasar pemerintah untuk UMKM sejatinya adalah upaya membangun ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Selama ini, belanja publik sering dianggap semata-mata sebagai instrumen fiskal untuk menggerakkan aktivitas ekonomi jangka pendek.
Padahal, jika dikelola dengan visi pembangunan jangka panjang, belanja publik bisa menjadi instrumen strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketika pemerintah membeli dari UMKM lokal, sesungguhnya negara sedang menanamkan investasi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Setiap transaksi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, dan memperkuat basis pajak daerah.
Dengan kata lain, pasar pemerintah bukan sekadar belanja, tetapi investasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Harapan: Saatnya UMKM Menjadi Mitra Utama Negara
Memaksimalkan pasar pemerintah bukanlah soal memberi keistimewaan bagi UMKM, melainkan soal menciptakan kesetaraan peluang dan kemandirian ekonomi nasional. Di tengah tantangan global seperti disrupsi rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi, memperkuat ekonomi domestik melalui penguatan UMKM dalam belanja publik merupakan langkah
strategis yang realistis dan berdampak luas.
Dengan dukungan regulasi yang berpihak, digitalisasi pengadaan yang transparan, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif, pasar pemerintah dapat menjadi jembatan bagi UMKM untuk naik kelas dari pelaku usaha lokal menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.
Arah kebijakan ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyatnya sendiri.